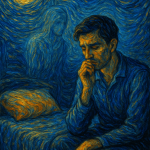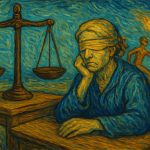Di sebuah sekolah dasar di Prefektur Niigata, Jepang, seorang guru bertanya kepada murid-muridnya: “Siapa yang ingin menjadi petani?” Beberapa tangan terangkat, tanpa malu, tanpa canggung, bahkan dengan bangga. Di sana, profesi petani tidak dilihat sebagai pekerjaan yang kotor, penuh lumpur, atau tertinggal. Petani adalah penjaga kehidupan, pewaris tanah, dan bagian dari tatanan sosial yang dihormati. Ini bukan sekadar idealisme romantik tentang pedesaan; ini adalah refleksi dari sistem nilai yang ditanamkan sejak anak-anak masih mengenakan seragam versi Jepang: sopan santun, rasa hormat, dan etika sosial, termasuk pada para petani.
Pendidikan moral di Jepang bukan sekadar pelajaran tambahan yang ditempelkan di ujung minggu. Ia terintegrasi dalam kurikulum nasional sebagai dōtoku kyōiku, pelajaran hidup yang mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari gaji bulanan, tetapi dari kontribusi terhadap kehidupan bersama. Dalam ruang ini, petani tidak hanya dijelaskan sebagai profesi, tapi sebagai penopang peradaban. Sejak kecil, anak-anak Jepang diajarkan bahwa makan siang mereka tidak jatuh dari langit; ada tangan yang menanam, memanen, dan mengantar. Inilah mengapa adab terhadap petani menjadi bagian dari pendidikan karakter. Sebagaimana ditulis oleh Daisaku Ikeda, filsuf dan pendidik Jepang, “Masyarakat yang tidak menghormati pembawa pangan adalah masyarakat yang kehilangan akar kemanusiaannya.”
Kontrasnya begitu mencolok ketika kita memalingkan pandangan ke Indonesia. Di negeri yang tanahnya disebut paling subur oleh van den Bosch pada masa tanam paksa, para pewaris bumi justru menjadi simbol kemiskinan. Petani dianggap profesi kelas bawah, lekat dengan citra inferioritas yang tak kunjung lepas. Seorang pelajar anak petani di desa-desa, misalnya, ketika ditanya cita-citanya, hampir pasti menjawab ingin jadi “pegawai” atau “kerja kantoran”, tak ada yang ingin jadi petani seperti orangtuanya, seolah menyebut “petani” adalah kutukan yang harus dijauhi. Mengapa stigma ini begitu melekat? Apakah kita sedang mewarisi trauma kolonial yang belum selesai?
Pada masa penjajahan, buruh tani adalah simbol dari mereka yang diperintah, ditindas, dan diperas keringatnya demi mesin-mesin kolonialisme. Tanah yang mereka garap bukan milik mereka, dan hasil panennya pun sering kali bukan untuk anak-anak mereka. Petani menjadi bayangan bisu dari sistem ketimpangan. Pasca kemerdekaan, meskipun struktur politik berubah, narasi penghinaan terhadap petani tak juga luruh. Bahkan kini, dalam era kapitalisme digital, ironi baru muncul: lulusan sarjana pertanian enggan menyentuh tanah. Saudara saya sendiri, lulusan fakultas pertanian, lebih memilih membuka toko kelontong daripada mengolah sawah milik keluarganya. Mungkin bukan hanya karena sawah itu tak menguntungkan, tapi karena sawah itu tak menjanjikan gengsi.
Ironisnya, di saat yang sama, para pengusaha kelas dunia, seperti Bill Gates justru memborong lahan pertanian lebih luas dari Jakarta. Mark Zuckerberg menanam investasi di peternakan sapi berteknologi tinggi di Hawaii. Jack Ma kembali ke desa, mendirikan pertanian organik, bukan hanya sebagai bisnis tapi juga sebagai warisan nilai. Bahkan David Beckham membuka lini makanan sehat dengan mantan ilmuwan NASA, percaya bahwa masa depan bukan pada layar digital, tapi pada sawah dan ladang. Apa yang mereka lihat, sementara generasi muda kita justru berpaling? Di tengah euforia kecerdasan buatan, mereka justru menjauh dari yang paling manusiawi: pangan.
Kita menyaksikan pertarungan sunyi antara yang digital dan yang mendasar. Anak-anak muda Indonesia sedang berlomba-lomba mempelajari manajemen, akuntansi, dan marketing, bidang yang dalam banyak aspek telah dikuasai oleh algoritma dan perangkat lunak. Tetapi siapa yang menguasai sektor pangan? Siapa yang ahli dalam mengolah tanah, menanam dengan cara lestari, dan memelihara ternak dengan penuh etika? Generasi kita gamang. Pendidikan kita tidak melahirkan kecintaan pada tanah, melainkan kecemasan akan keterpinggiran sosial. Padahal, seperti kata Wendell Berry, “Tanah bukan warisan dari leluhur, melainkan pinjaman dari anak cucu.” Lalu bagaimana jika yang meminjam tak tahu cara mengelola, bahkan tak mau mengakui nilai dari apa yang dipinjam?
Sudah saatnya kita membuka ruang pemikiran baru. Bahwa kemuliaan tidak selalu datang dari layar komputer, tetapi bisa tumbuh dari sepetak tanah yang dipelihara dengan cinta dan keberanian. Kita harus mendobrak sistem nilai yang menyamakan harga diri dengan profesi ber-jas, dan mulai membangun narasi baru tentang kehormatan: bahwa petani bukan orang kalah, melainkan penjaga kehidupan.
Apakah kita berani bermimpi tentang Indonesia yang mengembalikan kehormatan petani seperti Jepang? Apakah kita cukup berani untuk membayangkan sistem pendidikan yang tidak hanya mencetak pelamar kerja, tapi juga pecinta sawah dan ladang? Apakah kita bisa mengajarkan anak-anak kita bahwa profesi bukan tentang gengsi, tapi tentang kontribusi terhadap kehidupan?
Di tengah krisis pangan global dan percepatan digitalisasi, mungkinkah profesi petani justru menjadi simbol masa depan yang paling relevan dan bermartabat? Dan jika demikian, pertanyaan paling mendasar yang harus kita ajukan adalah: mungkinkah kita telah keliru selama ini dalam memaknai kesuksesan. (*)
- Timbangan Mendengkur - 23 Agustus 2025
- 5 Sajak Agustus, Suasana Kemerdekaan - 9 Agustus 2025
- Tanah yang Dilupakan - 13 Juli 2025