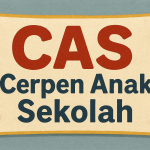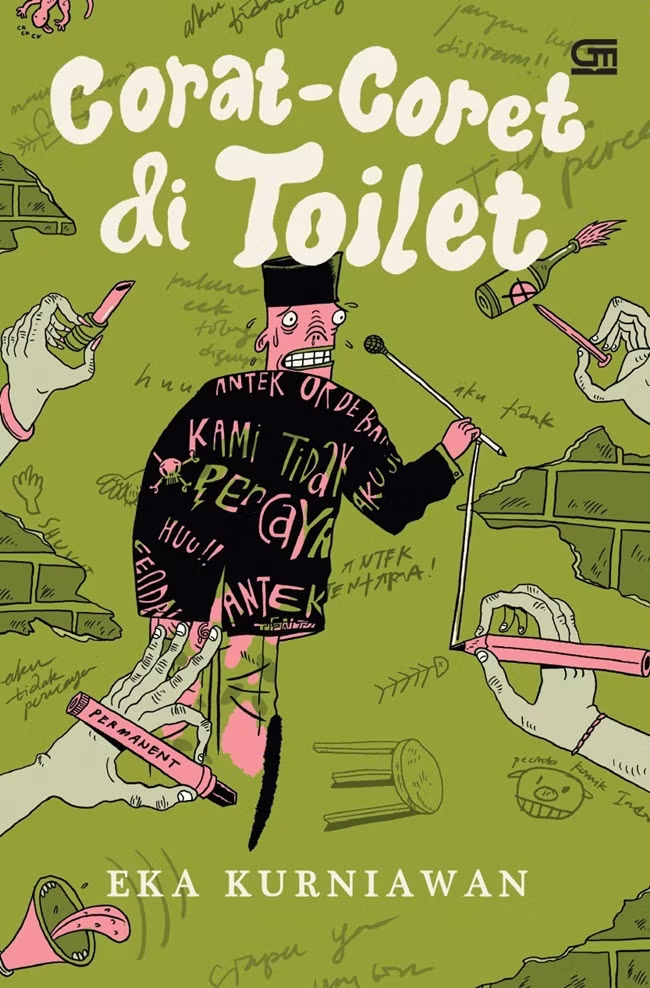KETIKA BUKU TIDAK LAGI BERBAHAYA: DEKADENSI INTELEKTUAL DALAM CERPEN “PETER PAN” KARYA EKA KURNIAWAN
Oleh: Try Widya Andini
Coba bayangkan seseorang mencuri mobil atau perhiasan, pasti polisi langsung turun tangan. Tetapi kalau yang dicuri adalah buku? Tidak ada yang peduli. Begitulah gambaran ironi dalam cerpen “Peter Pan” karya Eka Kurniawan. Peter Pan, si tokoh utama, sengaja mencuri buku bukan karena ia ingin membacanya, tetapi untuk membuktikan satu hal: buku sudah kehilangan nilainya di mata masyarakat. Tidak ada yang marah, tidak ada yang merasa kehilangan, seakan-akan buku tidak lebih dari benda mati yang tidak lagi berharga. Miris, bukan?
Respon masyarakat terhadap aksi Peter Pan semakin mempertegas ironi tersebut. Tidak ada reaksi marah, kepanikan, atau usaha untuk mencegah pencurian yang dilakukan secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa buku telah kehilangan perannya sebagai alat perlawanan intelektual, sesuatu yang dahulu ditakuti oleh rezim otoriter. Rizkita, dkk (2020), menyebutkan bahwa di masa lalu, buku yang memiliki muatan ideologi tertentu sering kali menjadi sasaran pengawasan dan pemusnahan karena penguasa memahami dampaknya terhadap opini publik. Namun, dalam konteks cerpen “Peter Pan,” sikap tidak peduli masyarakat terhadap pencurian buku mencerminkan bentuk kemunduran intelektual yang lebih serius: bukan karena adanya sensor yang membatasi akses terhadap buku, melainkan karena masyarakat sendiri yang telah kehilangan minat untuk membaca dan berpikir kritis.
Melalui cerpen ini, Eka Kurniawan mengkritisi kondisi intelektual masyarakat modern yang semakin abai terhadap pengetahuan tertulis. Buku, yang dahulu menjadi senjata utama dalam perlawanan terhadap ketidakadilan, kini hanya menjadi benda mati yang kehilangan pengaruh sosialnya. Buku bisa menggulingkan kekuasaan, membakar semangat revolusi, dan mengubah cara berpikir seseorang. Saking berbahayanya,menurut Rodin dkk (2024), beberapa buku bahkan pernah dilarang atau dibakar oleh penguasa yang takut akan isi di dalamnya.
Eka Kurniawan merupakan sastrawan Indonesia yang dikenal karena kritik sosial dalam karyanya. Lahir di Tasikmalaya pada tahun 1975, ia tumbuh dalam situasi politik yang penuh ketegangan di bawah pemerintahan Orde Baru. Menempuh pendidikan di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada semakin mengasah ketertarikannya pada isu sosial, sejarah, dan ketimpangan yang dialami rakyat kecil. Gaya khas Eka menggabungkan realisme magis dan humor satiris, sebagaimana terlihat dalam Cantik Itu Luka dan Lelaki Harimau, yang menyajikan perpaduan antara sejarah, mitos, dan kritik sosial. Selain novel, ia juga menulis cerpen yang sarat sindiran, seperti dalam “Corat-Coret di Toilet” yang menggambarkan absurditas kehidupan masyarakat. Salah satu cerpen terkenal dari kumpulan tersebut adalah “Peter Pan”, yang menyoroti lemahnya budaya literasi di Indonesia. Tokoh utamanya mencoba menarik perhatian publik dengan mencuri buku, berharap tindakannya memicu diskusi, tetapi justru tidak ada yang peduli. Kutipan, “Aku ingin membuktikan bahwa buku-buku tak lagi dianggap berharga… Tapi nyatanya, tak seorang pun peduli” (Kurniawan, 2000), menyoroti ironi bahwa ilmu pengetahuan yang seharusnya berharga malah diabaikan. Kritik seperti ini sering muncul dalam karya Eka, yang tidak hanya bertujuan menghibur, tetapi juga menggugah kesadaran pembaca akan ketimpangan sosial. Dengan pendekatan uniknya, Eka Kurniawan kerap disandingkan dengan sastrawan besar dunia dan tetap menjadi salah satu penulis paling berpengaruh di Indonesia saat ini.
Perubahan zaman membawa perubahan sikap terhadap literasi. Sekarang, buku justru terabaikan, tenggelam di tengah derasnya arus informasi digital yang serba instan. Orang lebih suka membaca ringkasan atau sekadar melihat cuplikan video singkat daripada benar-benar memahami sebuah gagasan lewat buku. Generasi muda yang seharusnya menjadi penerus pemikiran kritis justru lebih banyak mengonsumsi konten instan yang cepat terlupakan. Hal ini menjadi persoalan serius, karena tanpa pemikiran yang mendalam, manusia kehilangan kemampuannya untuk bertanya, mempertanyakan, dan mencari jawaban yang lebih bermakna.
Fenomena ini menggambarkan bagaimana masyarakat semakin jauh dari budaya literasi. Pendidikan pun ikut terseret dalam arus ini. Menurut Rizkita dkk (2020), saat ini sekolah dan universitas lebih fokus pada nilai dan sertifikasi daripada membangun pemikiran kritis. Mahasiswa yang seharusnya jadi garda terdepan dalam perubahan justru lebih sibuk mengejar gelar dan pekerjaan bergaji tinggi, sementara buku hanya menjadi pajangan atau pelengkap tugas akademik. Tidak sedikit dari mereka yang melihat membaca sebagai beban, bukan sebagai kebutuhan. Padahal, membaca bukan hanya tentang menelan informasi, tetapi tentang menganalisis, menghubungkan ide, dan membangun perspektif baru.
Di sisi lain, perkembangan teknologi yang seharusnya memperluas akses ilmu pengetahuan justru sering kali mempersempitnya. Algoritma media sosial lebih banyak mendorong konten viral yang dangkal daripada literasi mendalam. Orang lebih tertarik pada sensasi sesaat daripada refleksi mendalam. Akibatnya, daya pikir kritis menurun, dan masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh narasi yang dangkal dan manipulatif. Berita palsu dan teori konspirasi mudah menyebar, sementara literasi mendalam semakin langka. Menurut Pertiwi (2020), tanpa kebiasaan membaca yang baik, sulit bagi masyarakat untuk membedakan informasi yang valid dengan propaganda yang menyesatkan.
Pemerintah pun tidak banyak berbuat untuk membalikkan keadaan ini. Perpustakaan, yang seharusnya menjadi pusat literasi, sering kali terbengkalai. Banyak perpustakaan umum yang koleksinya usang dan kurang menarik bagi generasi muda. Akses terhadap buku berkualitas masih terbatas, dan literasi belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa. Tanpa dorongan dari sistem pendidikan dan kebijakan yang mendukung, sulit bagi masyarakat untuk membangun kebiasaan membaca yang kuat. Eddyono (2021), berpandangan bahwa seharusnya ada lebih banyak program yang mempromosikan literasi di sekolah dan di komunitas agar membaca tidak hanya menjadi kewajiban akademik, tetapi juga bagian dari gaya hidup.
Sebagai masyarakat yang peduli dengan masa depan intelektual bangsa, kita tidak bisa hanya berpangku tangan. Harus ada langkah nyata yang diambil untuk menghidupkan kembali budaya membaca. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyesuaikan literasi dengan zaman. Teknologi tidak bisa dihindari, tetapi bisa dimanfaatkan untuk mendorong minat baca. Buku digital, platform diskusi daring, serta media sosial yang dimanfaatkan secara positif dapat menjadi alat yang efektif dalam menumbuhkan kebiasaan membaca. Selain itu, komunitas literasi harus diperkuat agar orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap buku bisa saling berbagi dan menginspirasi.
Orang tua dan pendidik juga memegang peran penting dalam membentuk kebiasaan membaca sejak dini. Anak-anak harus dibiasakan untuk mengenal buku, bukan hanya sebagai tugas sekolah, tetapi juga sebagai aktivitas yang menyenangkan. Menciptakan lingkungan yang mendukung, seperti perpustakaan rumah, klub buku keluarga, atau sesi membaca bersama, dapat menjadi langkah awal yang berdampak besar. Jika membaca dianggap sebagai aktivitas yang menarik, maka anak-anak akan tumbuh dengan kesadaran bahwa buku adalah sumber ilmu yang berharga.
Selain itu, dunia akademik juga harus berubah. Kampus dan sekolah tidak boleh hanya mengejar hasil akademik yang instan. Kurikulum pendidikan harus lebih mendorong eksplorasi literasi yang lebih luas. Dosen dan guru perlu menginspirasi murid untuk berpikir kritis melalui buku, bukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi sebagai pemicu diskusi dan pemikiran reflektif. Dengan begitu, buku tidak hanya menjadi alat pembelajaran, tetapi juga jalan untuk menemukan gagasan baru yang bisa mengubah dunia.
Jika tren ini terus berlanjut, kita bisa menghadapi generasi yang tidak lagi memiliki ketertarikan terhadap literasi. Ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kemajuan bangsa secara keseluruhan. Tanpa budaya membaca yang kuat, inovasi akan melambat, dan masyarakat akan lebih mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak terverifikasi. Oleh karena itu, kita harus menjadikan membaca sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Lalu, apakah ini akhir dari era buku? Apakah literasi tradisional sudah tidak relevan di zaman digital? Atau, apakah kita hanya perlu mencari cara baru untuk menghidupkan kembali gairah membaca? Eka Kurniawan lewat cerpen “Peter Pan” seakan-akan menyindir kita: jika buku tak lagi dianggap penting, itu bukan hanya soal kehilangan benda fisiknya, tapi juga hilangnya semangat intelektual yang pernah membuat manusia berkembang. Kita harus mencari solusi untuk mengatasi fenomena ini, baik dengan menggabungkan teknologi dengan literasi maupun dengan membentuk kembali cara kita memperkenalkan buku kepada generasi muda.
Jika generasi sekarang terus mengabaikan buku, bukan tidak mungkin kita sedang menuju era baru yang lebih berbahaya, bukan karena larangan membaca, tetapi karena ketidakpedulian kita sendiri terhadap ilmu pengetahuan. Di masa depan, bukan hanya buku yang akan hilang, tetapi juga kebiasaan berpikir mendalam dan kritis yang menjadi dasar dari peradaban maju. Oleh karena itu, perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus mulai kembali membaca, menghidupkan diskusi yang bermakna, dan menantang diri kita untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga untuk mempertanyakan dan memahami lebih dalam. Jadi, apakah kita masih peduli? Atau kita hanya akan menjadi bagian dari generasi yang membiarkan kebodohan merajalela tanpa perlawanan?
Referensi
Eddyono, A. (2021). Perpustakaan dan Masa Depan Literasi di Indonesia. Jakarta: Literasi Nusantara.
Kurniawan, Eka. (2000). Peter Pan. Jakarta: Media Indonesia.
Pertiwi, S. (2021). Media Sosial dan Krisis Literasi: Sebuah Analisis Kritis. Yogyakarta: Pustaka Digital.
Rizkita, D., Junaedi, T., & Sos, M. (2020). Pendidikan dan Literasi: Tantangan di Era Digital. Bandung: Edukasi Press.Rodin, A., Rosaliya, N., & Amrullah, R. (2024). Buku yang Dilarang: Sejarah Sensor dan Pembungkaman Intelektual. Surabaya: Akademia Press.